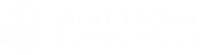Oleh: Rifky Gimnastiar (Mahasiswa Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam)
IAI At-Taqwa, Karya Mahasiswa – Maulid Nabi bukan sekadar seremonial tahunan yang dirayakan dengan gema shalawat dan barzanji. Bagi mahasiswa yang sekaligus santri, momentum ini adalah ruang kontemplasi, ruang dialog batin antara iman, ilmu, dan sejarah. Nabi Muhammad SAW hadir bukan hanya sebagai sosok religius, melainkan juga “superhero peradaban” yang berhasil mengangkat manusia dari lembah kegelapan jahiliyah menuju puncak cahaya keilmuan.
Sejarah mencatat, Muhammad lahir di tengah masyarakat yang rapuh secara moral dan sosial. Tradisi jahiliyah menempatkan manusia dalam degradasi kemanusiaan: perempuan dipandang rendah, anak perempuan dikubur hidup-hidup, dan perang suku menjadi kebanggaan. Dari reruntuhan peradaban inilah Muhammad hadir, bukan dengan pedang semata, melainkan dengan akhlak, strategi, dan visi besar yang melampaui zamannya.
Michael H. Hart dalam bukunya The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History menempatkan Muhammad di posisi pertama. Hart, seorang penulis non-Muslim, mengakui kepemimpinan Muhammad yang tidak hanya sukses secara spiritual, tetapi juga politis dan sosial. Pengakuan ini menjadi legitimasi bahwa Nabi tidak bisa direduksi hanya sebagai figur agama, melainkan sebagai pemimpin revolusi peradaban.
Strategi dakwah Muhammad adalah pelajaran tentang manajemen perubahan. Beliau memulai dengan pendekatan sembunyi-sembunyi, melatih fondasi iman di Dar al-Arqam. Baru setelah basis itu kokoh, dakwah dilakukan secara terbuka, menantang struktur dominasi Quraisy. Inilah logika strategi yang terukur: dari internalisasi nilai menuju ekspansi sosial. Suatu pendekatan yang sangat aktual hingga hari ini.
Ketika pasukan Islam harus berhadapan dengan jumlah musuh yang berlipat ganda, Muhammad menunjukkan kekuatan intelektual dan spiritual. Perang Badar menjadi bukti: hanya dengan 313 pasukan, kaum Muslim mampu menundukkan ribuan pasukan Quraisy. Kemenangan ini bukan sekadar kalkulasi militer, tetapi hasil dari strategi, doa, dan kepemimpinan visioner.
Di balik strategi militer, Muhammad mengajarkan pentingnya kesadaran kolektif. Perang bukanlah tujuan, melainkan sarana menegakkan keadilan. Beliau menolak menumpahkan darah tanpa alasan, bahkan dalam situasi perang sekalipun, etika tetap dijunjung tinggi. Tidak menebang pohon, tidak membunuh perempuan dan anak-anak—ajaran yang hari ini masih menjadi etika perang modern.
Momentum maulid adalah refleksi atas kepemimpinan yang bukan hanya teori, tetapi teladan nyata. Nabi bukan sekadar guru moral, melainkan aktor sejarah yang hidup bersama umatnya, merasakan lapar, susah, perang, dan damai. Kepemimpinannya adalah kepemimpinan partisipatif: bersama umat, bukan di atas umat.
Bagi mahasiswa-santri, ini adalah cermin. Bahwa ilmu bukan hanya tumpukan teori di kelas, melainkan harus menyatu dengan amal. Bahwa kepemimpinan bukan sekadar posisi, melainkan keteladanan yang dihidupi. Dalam diri Muhammad, teori dan praktik menyatu: qudwah sekaligus uswah.
Al-Qur’an menegaskan: “Wa mā Muhammadun illā rasūl” (QS. Ali Imran: 144). Muhammad hanyalah seorang Rasul, namun risalahnya menjadi lentera abadi. Kesadaran ini penting: kita tidak mengultuskannya secara berlebihan, tetapi meneladani ajarannya. Rasul adalah jalan, bukan tujuan. Tujuan tertinggi adalah Allah, sedangkan Muhammad adalah petunjuk yang menuntun manusia ke arah-Nya.
Jika ditelisik, kepemimpinan Muhammad adalah kepemimpinan berbasis visi transendental. Bukan sekadar membangun tatanan politik, tetapi membangun manusia. Bukan sekadar membebaskan dari dominasi Quraisy, tetapi membebaskan dari belenggu nafsu. Revolusi yang beliau pimpin adalah revolusi ruhani sekaligus sosial.
Maulid juga adalah momentum menghidupkan kembali narasi keilmuan. Muhammad mengubah orientasi manusia dari mitos menuju logos, dari dogma buta menuju nalar yang tercerahkan. Peradaban Islam yang lahir kemudian adalah buah dari revolusi ilmiah yang beliau tanamkan: “Iqra’”—bacalah. Sebuah kata sederhana yang meruntuhkan dinding kebodohan.
Hari ini, mahasiswa-santri dihadapkan pada “jahiliyah modern”: hedonisme, materialisme, dan krisis moral. Momentum maulid mengingatkan bahwa perjuangan intelektual harus dibarengi dengan spiritualitas. Tanpa iman, ilmu menjadi kering. Tanpa ilmu, iman bisa menjadi kaku. Muhammad mengajarkan keseimbangan: antara hati, akal, dan tindakan.
Dari perspektif ini, maulid bukan sekadar nostalgia sejarah, tetapi juga agenda perubahan. Santri yang belajar kitab kuning dan mahasiswa yang bergulat dengan teori modern harus menjadikan Muhammad sebagai jembatan: bagaimana tradisi dan modernitas dapat berdialog. Sebagaimana beliau memadukan wahyu dan akal, maka hari ini kita ditantang memadukan agama dan ilmu pengetahuan.
Metafora tentang Muhammad sebagai “superhero peradaban” bukanlah hiperbola. Beliau menyelamatkan manusia dari kehancuran moral, membangun etika universal, dan meninggalkan warisan nilai yang abadi. Namun, berbeda dengan superhero fiksi yang lahir dari komik, Muhammad adalah superhero nyata—darah, air mata, dan doa beliau menegaskan bahwa teladannya bukan khayalan.
Akhirnya, maulid adalah undangan untuk bersyukur: “Wa ammā bini‘mati rabbika faḥaddiṡ” (QS. Ad-Duha: 11). Nikmat terbesar itu adalah diutusnya Rasulullah. Syukur itu bukan hanya dengan perayaan, tetapi dengan melanjutkan misi beliau: menebar rahmat bagi semesta. Mahasiswa-santri, dengan bekal ilmu dan iman, dipanggil untuk menjadi pewaris perjuangan itu—menghadirkan kembali cahaya Muhammad di tengah dunia yang gelap.